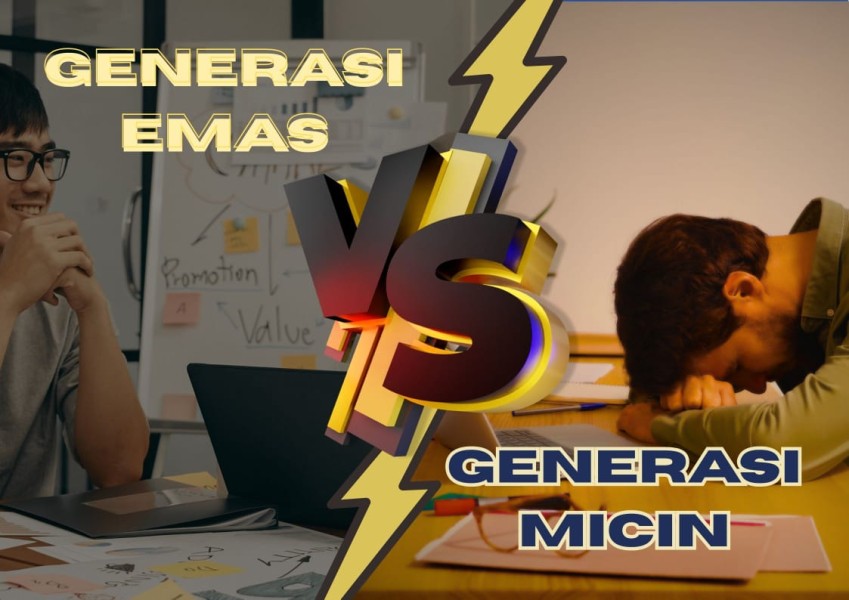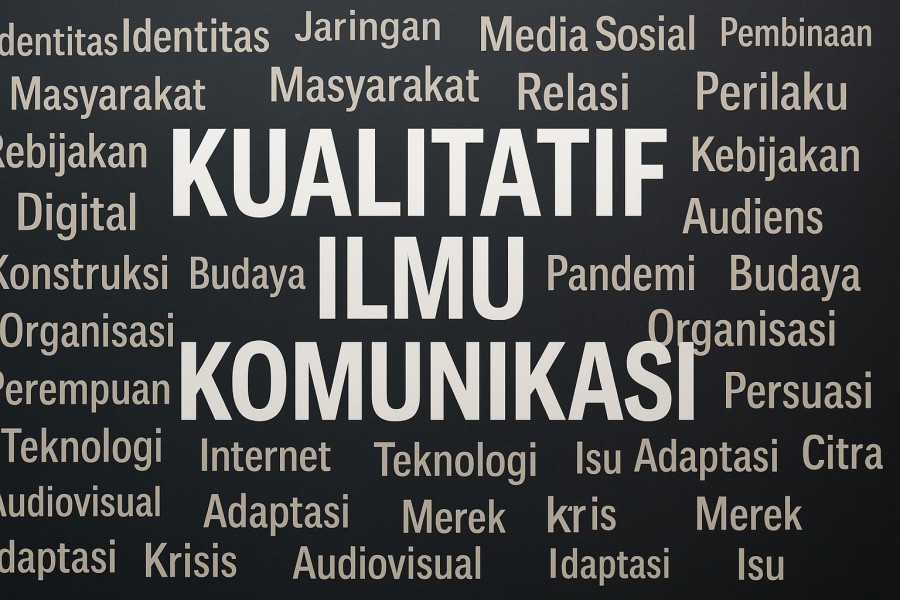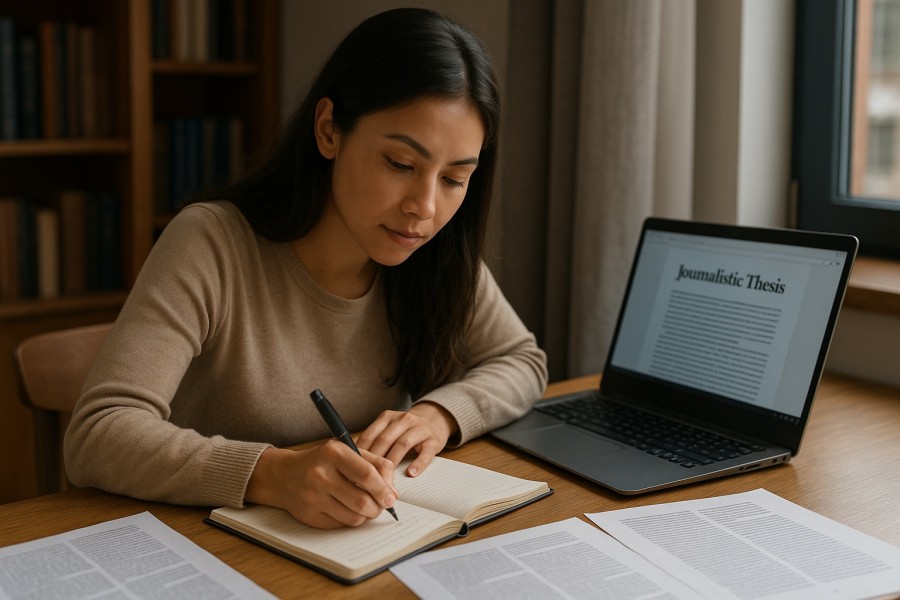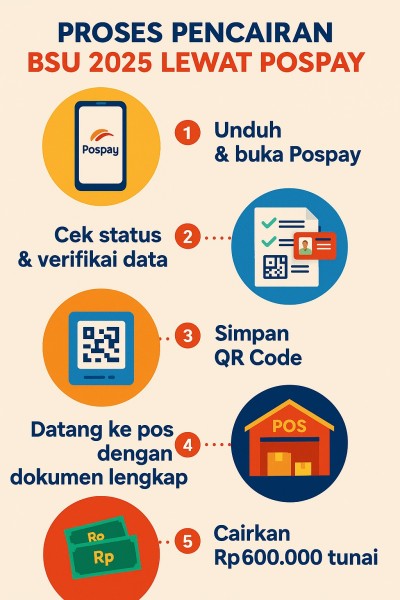Oleh: Muhammad Furqan Abdul Hadi, Mahasiswa S1 Jurnalistik Universitas Bengkulu
Setiap generasi merupakan cerminan dari zaman di mana mereka tumbuh dan berkembang. Mereka terbentuk oleh rentang waktu kelahiran yang sama, usia yang berdekatan, serta pengalaman kolektif terhadap peristiwa-peristiwa sejarah, sosial, maupun budaya yang khas pada masanya. Dari pengalaman bersama inilah kemudian lahir identitas, cara pandang, dan perilaku yang membedakan satu generasi dengan generasi lainnya. Perbedaan ini tidak hanya membentuk pola pikir, tetapi juga menghadirkan tantangan unik bagi tiap generasi. Namun, sering kali perbedaan tersebut justru menimbulkan kesenjangan pemahaman antar generasi.
Di tengah perkembangan zaman yang serba cepat, anak-anak muda hari ini hidup dalam dunia yang berbeda jauh dari generasi orang tua mereka. Ironisnya, alih-alih mendapat dukungan, mereka justru sering menjadi sasaran cibiran. Istilah generasi micin kerap dilontarkan untuk menggambarkan perilaku anak muda yang dianggap lemah mental, konsumtif, tidak tahan kritik, dan terlalu sibuk bermain gawai. Di sisi lain, negara mencanangkan visi Indonesia Emas 2045, sebuah impian besar yang sepenuhnya bertumpu pada bahu generasi muda. Pertanyaannya “bagaimana mungkin kita bisa membentuk generasi emas jika narasi dominan yang berkembang masih meremehkan mereka?”
Asal-Usul Stigma “Generasi Micin”
Sebutan generasi micin awalnya muncul sebagai lelucon di media sosial. Micin atau dalam bahasa latin monosodium glutamate diidentikkan dengan sesuatu yang "instan", "murahan", atau "merusak", dan kemudian digunakan untuk menyindir perilaku remaja dan pemuda yang dianggap tidak berkarakter kuat. Mereka dinilai terlalu gampang tersinggung (baper), terlalu banyak bermain gim online, hidup dalam "dunia maya", dan kurang peduli terhadap isu sosial.
Namun, pelabelan ini lama-lama berkembang menjadi stereotip yang berbahaya. Ketika anak muda membuat kesalahan, mereka cepat disalahkan. Ketika mereka bersuara, dianggap terlalu idealis atau belum cukup pengalaman. Kritik terhadap generasi muda menjadi semacam hiburan publik, baik di forum keluarga, ruang kelas, maupun media.
Kerap dibandingkan, Tanpa pengertian
Sering kali generasi muda dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang dianggap lebih disiplin, lebih pekerja keras, atau lebih tangguh menghadapi tekanan. Padahal, konteks sosial-ekonomi yang dihadapi kedua generasi sangat berbeda. Generasi muda hari ini tumbuh di tengah gejolaknya perkembangan digital, ketidakpastian ekonomi, dan tekanan sosial yang masif. Mereka bukan hanya harus bersaing di sekolah dan dunia kerja, tapi juga harus menjaga citra di media sosial, membangun personal branding, hingga mengatasi tekanan mental akibat standar sosial yang tidak realistis.
Contohnya, banyak anak muda yang merasa insecure karena belum mencapai "kesuksesan" seperti yang ditampilkan influencer atau tokoh publik di media sosial. Mereka merasa harus punya mobil, rumah, atau karier hebat sebelum usia 25 tahun. Tekanan ini nyata, dan berdampak serius terhadap kesehatan mental individu mereka.
Fakta Data ”Siapa Sebenarnya Generasi Z dan Milenial?”
Sebelum memberi label, mari lihat data. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, Generasi Z (lahir 1997–2012) dan Milenial (lahir 1981–1996) merupakan mayoritas penduduk produktif di Indonesia, mencakup lebih dari 50% populasi. Artinya, mereka adalah kekuatan utama yang akan menentukan arah bangsa ke depan.
Menurut Indeks Literasi Digital Kominfo 2023, Generasi Z menunjukkan kemampuan tinggi dalam mengakses, memahami, dan memproduksi informasi digital. Mereka tidak hanya aktif di media sosial, tetapi juga menggunakannya untuk edukasi, advokasi, dan kewirausahaan. Banyak di antara mereka yang menjalankan bisnis daring sejak SMA, membuat konten edukatif, atau terlibat dalam kampanye sosial seperti lingkungan, inklusi, dan kesehatan mental.
Lihat saja gerakan sosial seperti “ByeByePlasticBag” di Bali, yang digagas oleh dua remaja perempuan sejak usia 12 tahun. Atau komunitas “Sudah Dong” yang digerakkan anak muda untuk melawan bullying di sekolah. Ini hanya sebagian kecil dari potensi luar biasa generasi yang dianggap “micin”.
Terabaikannya Mental Generasi Muda
Salah satu dampak buruk dari stigma adalah gangguan psikologis. Label negatif dapat menciptakan tekanan mental, rasa rendah diri, dan hilangnya motivasi. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2018, sekitar 9,8% penduduk usia 15 tahun ke atas mengalami gangguan mental emosional, dengan prevalensi tertinggi di kalangan remaja dan dewasa muda. Riset Kementrian Kesehatan 2021 juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam kasus depresi dan kecemasan selama pandemi, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa.
Sayangnya, banyak orang dewasa masih menganggap kesehatan mental sebagai hal sepele. Ketika anak muda mengalami burnout atau kecemasan, mereka sering dianggap “manja”, “tidak bersyukur”, atau “kurang ibadah”. Padahal, justru mereka sedang membutuhkan dukungan dan ruang aman untuk bercerita, bukan stigma tambahan.
Mereka Butuh Kesempatan, Bukan Cacian
Generasi muda tidak butuh dinasihati terus-menerus, apalagi dicemooh. Mereka butuh didengar, dibimbing, dan diberi ruang untuk tumbuh. Pendidikan yang kolaboratif, lingkungan yang inklusif, dan ekosistem yang mendukung inovasi adalah fondasi penting untuk membentuk generasi emas.
Contohnya bisa kita lihat dari komunitas teknologi yang dibangun oleh anak muda seperti Dicoding, Coding Mum, atau Generation Girl, yang membuka akses keterampilan digital untuk generasi muda di berbagai daerah. Atau inisiatif Youth Manual yang membantu anak muda menemukan potensi diri lewat panduan karier dan pendidikan.
Semua ini membuktikan bahwa generasi muda bukan pasif, apalagi bodoh. Mereka sedang berproses dalam dunia yang jauh lebih kompleks dari masa lalu. Tugas generasi sebelumnya bukan untuk menghakimi, tapi untuk memfasilitasi.
Ayo Berkolaborasi, untuk Indonesia Emas 2045
Visi Indonesia Emas 2045 bukan slogan kosong. Untuk mencapainya, kita butuh investasi besar dalam pendidikan, kesehatan mental, pelatihan vokasi, dan literasi digital. Tapi yang tak kalah penting, kita perlu mengubah cara berpikir kita terhadap generasi muda.
Mengatakan “anak zaman sekarang terlalu lemah” tanpa melihat konteksnya adalah bentuk kemalasan berpikir. Menyebut mereka "micin" tanpa memberi solusi hanya akan menjauhkan kita dari masa depan yang kita impikan.
Emas tidak muncul dari cacian. Ia dibentuk melalui tempaan, bimbingan, dan kepercayaan. Jika kita terus melekatkan label negatif pada generasi muda, maka sesungguhnya kita sedang menggali lubang untuk masa depan kita sendiri.
Mari berhenti menyebut mereka generasi micin. Sebaliknya, mulai lihat potensi mereka sebagai generasi yang melek teknologi, punya empati sosial, dan mampu beradaptasi di dunia yang berubah cepat. Dengan pendekatan yang tepat, mereka bukan hanya akan menjadi emas mereka akan menjadi permata yang mengangkat martabat bangsa. ***