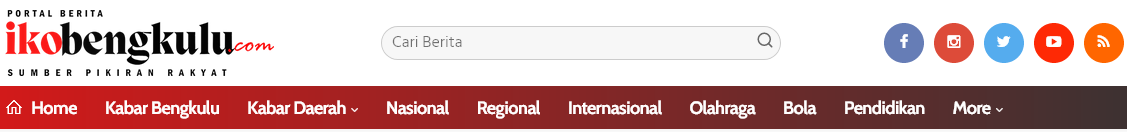Dua pemilihan umum terakhir di Indonesia diwarnai oleh perang julukan di media sosial antara pendukung Presiden Joko Widodo dan rival utamanya, Prabowo Subianto. Pendukung Jokowi dijuluki "cebong," singkatan dari kecebong atau berudu, sementara pendukung Prabowo diolok-olok dengan sebutan "kampret," yang merujuk pada kelelawar kecil. Kedua julukan tersebut merendahkan IQ lawan yang dianggap lebih rendah.
Namun, menjelang pemilu 2024 pada 14 Februari, situasinya berbeda. Dengan Jokowi yang tidak bisa mencalonkan diri lagi, ia dan Prabowo telah bergabung, sehingga sebagian besar komentar polarisasi terfokus pada upaya Jokowi mempertahankan kekuasaan dengan mengusung Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo.

Meski pendukungnya percaya Jokowi bertindak netral dan adil dalam menyambut pemilu dan melanjutkan agenda kerjanya, ada kekecewaan dan kemarahan dari mereka yang melihat pencalonan Gibran sebagai ilegal dan inkonstitusional, dengan frasa seperti "cacat hukum," "cacat moral," atau "cacat etika" sering digunakan.
Dalam proyek kami untuk memantau ujaran kebencian dan polarisasi online, kami mengambil sampel dan menganalisis sekitar 42.000 postingan antara September dan Desember 2023 dari X, Facebook, Instagram, dan artikel dari situs kolaborasi pemeriksaan fakta dengan menggunakan kata kunci yang dipilih untuk menangkap toksisitas dan identitas.
Kemarahan terhadap Jokowi dapat dipandang sebagai respons alami terhadap upayanya bertahan di kekuasaan, pertama dengan menunda pemilu umum, kemudian memperpanjang masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga, menggabungkan basis pendukung Prabowo dengan miliknya sendiri dengan nama "Projo", dan akhirnya, menominasikan Gibran sebagai kandidat wakil presiden.
Polarisasi antara pendukung Jokowi dan anti-Jokowi seringkali menciptakan bentrokan opini yang keras dan ketegangan di ruang siber.
Pesan positif tentang pencapaian pemerintah diimbangi dengan kecaman dan kritik terhadap kebijakan yang dianggap kontroversial.
Kontroversi terbesar adalah keputusan Mahkamah Konstitusi, yang dipimpin oleh saudara ipar Jokowi, Anwar Usman, yang memperbolehkan Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo. Setelah keputusan itu, hashtag #MahkamahKeluarga sebagai sindiran untuk Mahkamah Konstitusi mulai muncul sering kali. Hashtag lain adalah #Kamimuak yang diungkapkan sebagai respons terhadap kemarahan netizen terhadap manuver politik keluarga Jokowi.
Dinamika politik modern yang menjadikan media sosial sebagai medan pertempuran untuk opini dan kepercayaan politik, dipersulit oleh influencer yang secara sukarela atau berdasarkan kontrak, telah mengungkapkan pendapat mereka tentang tindakan Jokowi.
Keterlibatan influencer dalam acara peresmian Rumah Besar Akademi Militer Magelang pada 2 Februari memperkuat pemisahan kubu pro dan anti Jokowi.
Acara ini memicu pertengkaran di media sosial karena Jokowi dan Prabowo menggunakan acara dan fasilitas pemerintah untuk peresmian, dan kebanyakan postingan influencer hanya menyebutkan "kesederhanaan" dan "kepemimpinan besar" Jokowi dan Prabowo.
Kesalahpahaman tentang Polar
Berdasarkan pengamatan kami setelah pemilu 2019, ada kesalahpahaman tentang polarisasi online karena media mainstream hanya fokus pada analisis jaringan sosial data X (sebelumnya Twitter) yang menunjukkan dua kelompok besar percakapan. Namun, walaupun perc
akapan di X tentang isu politik terpolarisasi, ini tidak serta-merta berarti masyarakat itu sendiri terpolarisasi.
Ketergantungan berat pada analisis jaringan sosial Twitter dalam diskusi publik sejalan dengan tujuan pemerintah Indonesia mengendalikan narasi Indonesia yang bersatu dan obsesi untuk menginternalisasi ideologi negara Pancasila.
Sebagai hasilnya, kebijakan budaya pemerintah tentang Pancasila, berdasarkan definisi dan interpretasi Pancasila sendiri, harus diikuti oleh warga negara. Di bawah kebijakan ini, bahkan gaya berpakaian yang berbeda, seperti memakai hijab panjang bagi wanita atau menumbuhkan jenggot bagi pria Muslim, berpotensi dilabeli sebagai radikal.
Setiap siklus pemilihan, terjadi peningkatan ujaran kebencian yang ditujukan pada kelompok minoritas, seringkali dipicu oleh informasi salah dan disinformasi. Lonjakan negativitas ini dapat berkontribusi pada pemilu.
Salah satu cara untuk menanggulangi ini adalah bagi media untuk berkolaborasi dengan universitas dalam merancang kerangka pemantauan untuk menganalisis dan menyajikan data secara sistematis di platform khusus.
Temuan dari upaya pemantauan ini kemudian bisa dijadikan peta jalan bagi media untuk menghasilkan konten jurnalistik yang mempromosikan keberagaman dan mendukung hak-hak kelompok minoritas. Data ini dapat membantu mencegah amplifikasi narasi yang tidak sengaja yang memperkuat stigma dan diskriminasi, terutama yang dipropagandakan oleh faksi politik tertentu.
Dengan menggunakan wawasan dari pemantauan, outlet media massa dapat mengidentifikasi tren penggunaan ujaran kebencian dan menghindari memperkuat pesan yang memperkuat stereotip negatif terhadap kelompok minoritas.
Pendekatan pemantauan ini bisa menjadi sumber daya berharga tidak hanya bagi media, tetapi juga bagi badan pemantau pemilu, dewan pers, platform media sosial, dan pembela hak minoritas.
Dengan demikian, entitas-entitas ini dapat secara proaktif mengantisipasi dan menangani ujaran kebencian, mengurangi dampaknya terhadap polarisasi sosial.***
Ika Idris adalah profesor asosiasi di program Kebijakan Publik & Manajemen, Universitas Monash Indonesia. Ia merupakan co-author dari "Demokrasi yang Salah Arah di Asia Tenggara: Propaganda Digital di Malaysia dan Indonesia".
Derry Wijaya adalah profesor asosiasi di Program Data Science, Universitas Monash Indonesia. Ia adalah co-direktur Monash Data & Democracy Research Hub.
Prasetia Pratama adalah peneliti di Monash Data & Democracy Research Hub.
Musa Wijanarko adalah ilmuwan data di Monash Data & Democracy Research Hub.