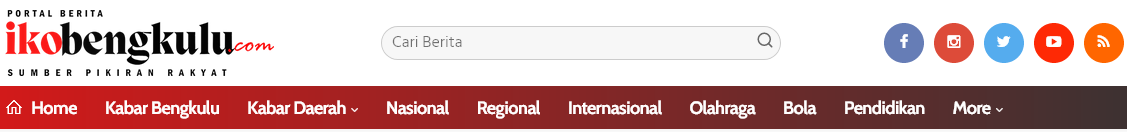Oleh: Yulia Indrawati Sari, Elisabeth A.S. Dewi, dan A. A. S. Dyah Ayunda N. A - Unika Parahyangan Bandung
TENUN tradisional berpotensi menjadi solusi pengentasan kemiskinan ekstrem di pedesaan Indonesia, meskipun solusi ini tidak dapat diterapkan secara universal.
Ketika tragedi menghampiri sahabatnya yang bekerja ilegal di luar negeri, Diana Timoria terdorong untuk mengambil tindakan signifikan. Di Pulau Sumba, Indonesia Timur, kondisi ekonomi yang sulit mendorong banyak remaja untuk memalsukan identitas guna memenuhi syarat usia kerja di luar negeri.
Akibatnya, mereka sering menjadi korban kejahatan karena ketiadaan dokumen resmi. Dalam enam bulan tahun 2021, tercatat 67 pekerja ilegal dari Sumba meninggal di luar negeri.
Dengan tingkat kemiskinan yang hampir dua kali lipat dibandingkan rata-rata nasional, penduduk Pulau Sumba hidup dengan penghasilan di bawah Rp. 30.000,- per hari. Pulau ini merupakan salah satu kontributor terbesar pekerja ilegal di Indonesia, namun juga terkenal dengan kain ikatnya yang berharga hingga jutaan rupiah per lembar. Tantangan utama adalah menarik pembeli ke penjual kain ikat ini.
Timoria mendirikan Komunitas Kandunu, sebuah komunitas penenun muda yang berfokus pada produksi kain ikat untuk memberdayakan perempuan sekaligus meningkatkan kesadaran tentang risiko migrasi ilegal. Komunitas ini terdiri dari anggota muda, baik pria maupun wanita, serta para lansia yang berbagi pengetahuan dan keterampilan menenun, sejarah, serta informasi tentang risiko migrasi ilegal.
Namun, keluar dari jerat kemiskinan mungkin membutuhkan lebih dari sekadar penghasilan dari menenun. Agustina Ronga Padak, seorang penenun di Sumba, menggambarkan menenun sebagai bagian penting dari kehidupan sosial dan budayanya. Meskipun demikian, pekerjaan ini tidak cukup menguntungkan untuk mendukung kehidupan keluarganya.
Perempuan Sumba, termasuk Agustina, menjalankan berbagai peran dari bertani hingga mengurus rumah tangga. Mereka menghadapi tantangan gagal panen dan surplus produksi yang minim. Memproduksi selembar kain ikat membutuhkan waktu hingga satu bulan, ditambah dengan keterbatasan akses pasar dan ketidakpastian pasar yang tinggi.
Beberapa organisasi masyarakat sipil berusaha memberdayakan perempuan di Sumba, namun terkendala oleh anggaran yang terbatas dan wilayah operasi yang luas. Efektivitas program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Sumba juga dipertanyakan, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur yang kurang mengakomodasi kebutuhan spesifik komunitas setempat.
Tanpa kebijakan pemerintah yang menyasar kebutuhan spesifik Sumba, masalah migrasi ilegal dan kemiskinan di wilayah ini diperkirakan akan terus berlanjut. Inisiatif seperti Komunitas Kandunu menjadi langkah penting dalam upaya pemberdayaan dan penyadaran, namun dukungan yang lebih luas dan terkoordinasi diperlukan untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Pulau Sumba.***
Yulia Indrawati Sari, Elisabeth A.S. Dewi, dan A. A. S. Dyah Ayunda N. A. adalah dosen di Departemen Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan. Yulia I Sari memiliki minat penelitian tentang Gender, LSM, dan Lingkungan. Elisabeth A.S. Dewi berfokus pada Gender dalam Hubungan Internasional, LSM, dan migrasi. Dyah tertarik pada Gender, Lingkungan, dan Ekonomi Politik Internasional.
Proyek penelitian ini didukung oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK).